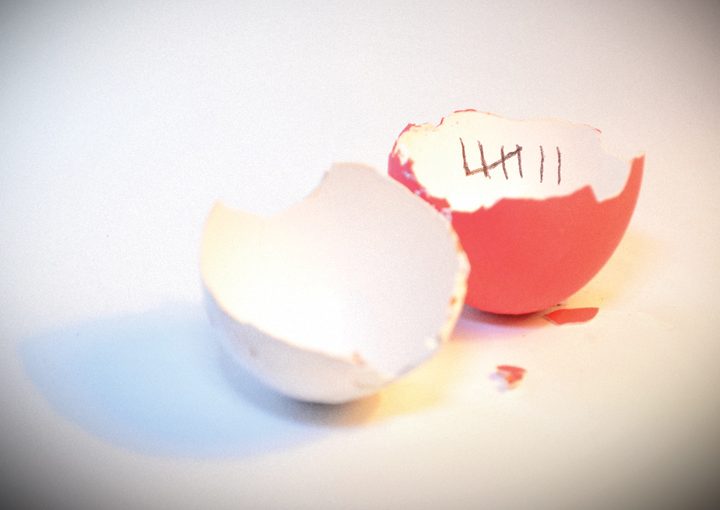![]()
JAKARTA (IndependensI.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar untuk mencari pemimpin secara demokratis, yang sesuai dengan pilihan rakyat. Namun, tidak sedikit kelompok yang menghalalkan berbagai cara demi kemenangan calon unggulannya.
Isu SARA sering digunakan untuk memojokkan calon tertentu. Hal ini amat berbahaya karena berpotensi menyulut radikalisme dan perang saudara di negeri yang penduduknya beragam ini.
“Sebagai negara majemuk, potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat sangat tinggi, apalagi jelang digelarnya Pilkada Serentak. Karena itu, pemerintah, terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mesti mewaspadai kemungkinan itu sedini mungkin,” ujar salah satu anggota kelompok ahli BNPT, Prof Dr Syaiful Bakhri, SH, MH, di Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Menurutnya, masyarakat itu terbagi dalam tiga lapisan yaitu elit, menengah, dan akar rumput (bawah). Dari ketiga lapisan itu, lapisan akar rumput yang paling mudah terprovokasi, sementara kalangan elit adalah kelompok yang bisa memprovokasi, sedangkan kelompok menengah relatif netral dan tidak terlalu mempersoalkan siapa yang mau jadi pemimpin.
“Kalangan kelas atas biasanya punya desain untuk mempertahankan posisi mereka. Caranya dengan masuk partai politik dan pergaulan elit lainnya. Meski jumlahnya sedikit, kalangan atas yang memiliki uang inilah yang bisa kerjasama atau membiayai provokator,” jelas pria yang juga rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai terjadinya provokasi dan kampanya hitam, apalagi mengatasnamakan SARA dalam Pilkada Serentak nanti. Semua harus sepakat untuk mempertahankan kondisi seperti sekarang ini yaitu Indonesia damai, tenteram dan bahagia, sebagai kepentingan nasional yang mutlak.
Selama ini, lanjut Syaiful, Indonesia sudah berjalan dengan baik dan telah berpengalaman menjalankan pesta demokrasi terbuka, baik itu Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sebanyak empat periode. Dalam pengalamannya, pada penyelenggaraan pesta demokrasi itu selalu terjadi gesekan tapi tidak menimbulkan konflik yang bersifat nasional, tapi hanya kedaerahan.
Ia meminta, kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus berfungsi dengan baik selama mengawal pelaksaan pesta demokrasi itu. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga sekecil apapun kemungkinan terjadinya gesekan bisa diantisipasi dari tingkat paling bawah.
“Perebutan kekuasaan melalui Pemilu ini khan konstitusional, maka hasilnya pun konstiutisional. Kalau hasilnya konstitusional maka yang kalah pasti menerimanya. Bila ada banyak catatan alasan kekalahan, maka bisa dilakukan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Kalau selesai di MK maka juga semuanya akan berakhir. Itulah ciri bahwa kewenangan konstitusional ada pada masyarakat. Saya kira masyarakat kita sudah dewasa dan memahami hal ini,” paparnya.
Mantan Wakil Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 menilai, keberadaan pengamat juga bisa menjadi pemicu terjadinya keributan saat pelaksaan pemilu. Ia melihat, banyak pengamat kadang datangnya secara mendadak dan malah tidak punya kompetensi bisa tampil di media. Bahkan diantara mereka kemampuan narasinya juga payah ditambah logikanya yang sempit.
Pengamat yang seperti inilah yang harus diawasi, karena ia bisa menjadi provokator yang bisa menyulut ketidakpuasan di masyarakat. Apalagi pengamat tersebut berbicara tergantung order.
“Apakah benar orang yang sekolahnya ekonomi, politik, sosial, hukum, bisa menjadi pengamat? Ilmu itu spesifik keahliannya. Orang yang punya potensi keahlian spesifik itulah yang harusnya bicara, Kalau tidak bisa mengakibatkan sentimen dan kontroversi di masyarakat. Belum lagi kalau pengamat itu by order. Pengamat seperti ini bisa jadi hanya akan menambah emosional masyarakat,” terang Syaiful.
Begitu juga lembaga survei, semua harus dilakukan secara akademik dan terbuka. Seharusnya hasil survei jangan dipublikasi dan hasilnya digunakan untuk merancang program calon atau partai politik tertentu. Pasalnya, survei itu dilakukan dengan metode berbeda-beda sehingga hasil survei pun tidak sama. Itu bisa mengganggu harmonisasi dan gampang memancing keributan di masyarakat.
Ia menyarankan agar dikembangkan seminar akademik terbuka. Seperti di Papua, di sana bukan LSM dan lembaga survei yang menentukan, tapi bisa dilakukan diskusi karena ada beberapa partai, juga bagaimana pemilihan noken. Beda dengan daerah lain yang banyak terdapat universitas.
Menurutnya, universitas bisa dirangkul dan digerakkan sebagai menara gading keilmuan untuk memberi pencerahan untuk melakukan survei. Memang kadang-kadang hasil survei yang dilakukan universita berlawanan dengan hasil survei dan pengamat. Tapi itulah bingkai yang harus diperhatikan.
“Kita semuanya harus jadi ‘polisi’ bagi negeri kita, bukan hanya polisi berseragam itu, tapi diri kita dan masyarakat. Dengan pembelajaran yang bagus dan metodologi yang logis, maka kita dan masyarakat akan bisa menjaga sendiri sehingga tidak mudah termakan provokasi. Karena betapa mahalnya provokasi itu karena akibatnya adalah kerusakan harta benda, mungkin nyawa, dan itu tidak bisa dipulihkan. Siapa yang akan menggantinya? Akhirnya korbannya makin panjang,” kata Prof Syaiful Bakhri.